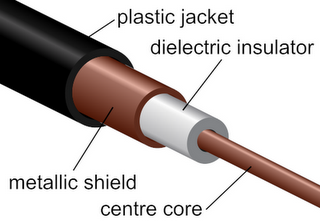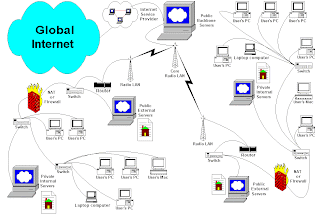“AKU sudah resmi jadi orang miskin,”
katanya, sambil memperlihatkan Kartu Tanda Miskin, yang baru diperolehnya dari
kelurahan. “Lega rasanya, karena setelah bertahun-tahun hidup miskin, akhirnya
mendapat pengakuan juga.”
Kartu Tanda Miskin itu masih bersih, licin, dan mengkilat karena
di-laminating. Dengan perasaan bahagia ia menyimpan kartu itu di dompetnya
yang lecek dan kosong.
“Nanti, bila aku pingin berbelanja, aku tinggal menggeseknya.”
Diam-diam
aku suka mengintip rumah orang miskin itu. Ia sering duduk melamun, sementara
anak-anaknya yang dekil bermain riang menahan lapar. “Kelak, mereka pasti akan
menjadi orang miskin yang baik dan sukses,” gumamnya.
Suatu sore, aku melihat orang miskin itu menikmati teh pahit bersama
istrinya. Kudengar orang miskin itu berkata mesra, “Ceritakan kisah paling
lucu dalam hidup kita….”
“Ialah ketika aku dan anak-anak begitu kelaparan, lalu menyembelihmu,”
jawab istrinya.
Mereka pun tertawa.
Aku selalu iri menyaksikan kebahagiaan mereka.
Orang miskin itu dikenal ulet. Ia mau bekerja serabutan apa saja. Jadi
tukang becak, kuli angkut, buruh bangunan, pemulung, tukang parkir. Pendeknya,
siang malam ia membanting tulang, tapi alhamdulillah tetap miskin juga.
“Barangkali aku memang run-temurun dikutuk jadi orang miskin,”ujarnya, tiap
kali ingat ayahnya yang miskin, kakeknya yang miskin, juga simbah buyutnya yang
miskin.
Ia pernah mendatangi dukun, berharap bisa mengubah garis buruk tangannya.
“Kamu memang punya bakat jadi orang miskin,” kata dukun itu. “Mestinya kamu
bersyukur, karena tidak setiap orang punya bakat miskin seperti kamu.”
Kudengar, sejak itulah, orang miskin itu berusaha konsisten miskin.
Pernah, dengan malu-malu, ia berbisik padaku. “Kadang bosan juga aku jadi
orang miskin. Aku pernah berniat memelihara tuyul atau babi ngepet. Aku pernah
juga hendak jadi pelawak, agar sukses dan kaya,” katanya. “Kamu tahu kan, tak
perlu lucu jadi pelawak. Cukup bermodal tampang bego dan mau dihina-hina.”
“Lalu kenapa kau tak jadi pelawak saja?”
Ia mendadak terlihat sedih, lalu bercerita, “Aku kenal orang miskin yang
jadi pelawak. Bertahun-tahun ia jadi pelawak, tapi tak pernah ada yang
tersenyum menyaksikannnya di panggung. Baru ketika ia mati, semua orang
tertawa.”
Orang miskin itu pernah kerja jadi badut. Kostumnya rombeng, dan
menyedihkan. Setiap menghibur di acara ulang tahun,
anak-anak yang menyaksikan atraksinya selalu menangis ketakutan.
“Barangkali kemiskinan memang bukan hiburan yang menyenangkan buat
anak-anak,” ujarnya membela diri, ketika akhirnya ia dipecat jadi badut.
Kadang-kadang, ketika merasa sedih dan lapar, orang miskin itu suka
mengibur diri di depan kaca dengan gerakan-gerakan badut paling lucu yang tak
pernah bisa membuatnya tertawa.
Orang miskin itu akrab sekali dengan lapar. Setiap kali lapar berkunjung,
orang miskin itu selalu mengajaknya berkelakar untuk sekadar melupakan
penderitaan. Atau, seringkali, orang miskin itu mengajak lapar bermain
teka-teki, untuk menghibur diri. Ada satu teka-teki yang selalu diulang-ulang
setiap kali lapar datang bertandang.
“Hiburan apa yang paling menyenangkan ketika lapar?” Dan orang miskin itu
akan menjawabnya sendiri, “Musik keroncongan.”
Dan lapar akan terpingkal-pingkal, sambil menggelitiki perutnya.
Yang menyenangkan, orang miskin itu memang suka melucu. Ia kerap
menceritakan kisah orang miskin yang sukses, kepadaku. “Aku punya kolega orang miskin
yang aku kagumi,” katanya. “Dia merintis karier jadi pengemis untuk membesarkan
empat anaknya. Sekarang satu anaknya di ITB, satu di UI, satu di UGM, dan
satunya lagi di Undip.”
“Wah, hebat banget!” ujarku. “Semua kuliah, ya?”
“Tidak. Semua jadi pengemis di kampus itu.”
Orang miskin itu sendiri punya tiga anak yang masih kecil-kecil. Paling
tua berumur 8 tahun, dan bungsunya belum genap 6 tahun. “Aku ingin mereka juga
menjadi orang miskin yang baik dan benar sesuai ketentuan undang-undang.
Setidaknya bisa mengamalkan kemiskinan mereka secara adil dan beradab
berdasarkan Pancasila dan UUD 45,” begitu ia sering berkata, yang kedengaran
seperti bercanda. “Itulah sebabnya aku tak ingin mereka jadi pengemis!”
Tapi, seringkali kuperhatikan ia begitu bahagia, ketika anak-anaknya
memberinya recehan. Hasil dari mengemis.
Pernah suatu malam kami nongkrong di warung pinggir kali. Bila lagi punya
uang hasil anak-anaknya mengemis, ia memang suka memanjakan diri menikmati
kopi. “Orang miskin perlu juga sesekali nyantai, kan? Lagi pula, beginilah
nikmatnya jadi orang miskin. Punya banyak waktu buat leha-leha. Makanya,
sekali-kali, cobalah jadi orang miskin,” ujarnya, sambil menepuk-nepuk
pundakku. “Kalau kamu miskin, kamu akan punya cukup tabungan penderitaan,
yang bisa digunakan untuk membiayaimu sepanjang hidup. Kamu bakalan punya
cadangan kesedihan yang melimpah. Jadi kamu nggak kaget kalau susah.” Kemudian
pelan-pelan ia menyeruput kopinya penuh kenikmatan.
Saat-saat seperti itulah, diam-diam, aku suka mengamati wajahnya.
Wajah orang miskin itu mengingatkanku pada wajah yang selalu muncul setiap
kali aku berkaca. Dalam cermin itu kadang ia menggodaku dengan gaya badut
paling lucu yang tak pernah membuatku tertawa. Bahkan, setiap kali ia meniru
gerakanku, aku selalu pura-pura tak melihatnya.
Pernah, suatu malam, aku melihat bayangan orang miskin itu keluar dari
dalam cermin, berjalan mondar-mandir, batuk-batuk kecil minta diperhatikan.
Ketika aku terus diam saja, kulihat ia kembali masuk dengan wajah kecewa.
Sejak itu, bila aku berkaca, aku kerap melihatnya tengah berusaha
menyembunyikan isak tangisnya.
Ada saat-saat di mana kuperhatikan wajah orang miskin itu diliputi
kesedihan. “Jangan salah paham,” katanya. “Aku sedih bukan karena aku miskin.
Aku sedih karena banyak sekali orang yang malu mengakui miskin. Banyak sekali
orang bertambah miskin karena selalu berusaha agar tidak tampak miskin.”
Entah kenapa, saat itu mendadak aku merasa kikuk dengan penampilanku yang
perlente. Sejak itu pula aku jadi tak terlalu suka berkaca.
Bila lagi sedih orang miskin itu suka datang ke pengajian. Tuhan
memang bisa menjadi hiburan menyenangkan buat orang yang lagi kesusahan,
katanya. Ia akan terkantuk-kantuk sepanjang ceramah, tapi langsung semangat
begitu makanan dibagikan.
Ada lagi satu cerita, yang suka diulangnya padaku:
Suatu malam ada seorang pencuri menyatroni rumah orang miskin. Mengetahui
hal itu, si miskin segera sembunyi. Tapi pencuri itu memergoki dan
membentaknya, “Kenapa kamu sembunyi?” Dengan ketakutan si orang miskin
menjawab, “Aku malu, karena aku tak punya apa pun yang bisa kamu curi.”
Ia mendengar kisah itu dalam sebuah pengajian. “Kisah itu selalu membuatku
punya alasan untuk bahagia jadi orang miskin,” begitu ia selalu mengakhiri
cerita.
Orang miskin itu pernah ditangkap polisi. Saat itu, di kampung memang
terjadi beberapa kali pencurian, dan sudah sepatutnyalah orang miskin itu
dicurigai. Ia diinterogasi dan digebugi. Dua hari kemudian baru dibebaskan.
Kabarnya ia diberi uang agar tak menuntut. Berminggu-minggu wajahnya bonyok dan
memar. “Beginilah enaknya jadi orang miskin,” katanya. “Dituduh mencuri,
dipukuli, dan dikasih duit!”
Sejak itu, setiap kali ada yang kecurian, orang miskin itu selalu mengakui
kalau ia pelakunya. Dengan harapan ia kembali dipukuli.
Banyak orang berkerumun sore itu. “Ada yang mati,” kata seseorang. Kukira
orang miskin itu tewas dipukuli. Ternyata bukan. “Itu perempuan yang kemarin
baru melahirkan. Anaknya sudah selusin, suaminya minggat, dan ia merasa repot
kalau mesti menghidupi satu jabang bayi lagi. Makanya ia memilih membakar
diri.”
Perempuan itu ditemukan mati gosong, sambil mendekap bayi yang disusuinya.
Orang-orang yang mengangkat mayatnya bersumpah, kalau air susu perempuan itu
masih menetes-netes dari putingnya.
Sepertinya ini memang lagi musim orang miskin bunuh diri. Dua hari lalu,
ada seorang ibu sengaja menabrakkan diri ke kereta api sambil menggendong dua
anaknya. Ada lagi sekeluarga orang miskin yang kompak menenggak racun. Ada juga
suami istri gantung diri karena bosan dililit hutang.
“Tak gampang memang jadi orang miskin,” ujar orang miskin itu. “Hanya orang
miskin gadungan yang mau mati bunuh diri. Untunglah, sekarang saya sudah resmi
jadi orang miskin,” ujarnya sembari menepuk-nepuk dompet di pantat teposnya, di
mana Kartu Tanda Miskin itu dirawatnya. “Ini bukti kalau aku orang miskin
sejati.”
Orang miskin punya ponsel itu biasa. Hanya orang-orang miskin yang
ketinggalan zaman saja yang tak mau berponsel. Tapi aku tetap saja kaget
ketika orang miskin itu muncul di rumahku sambil menenteng telepon genggam.
“Orang yang sudah resmi miskin seperti aku, boleh dong bergaya!” katanya
dengan gagah. Lalu ia sibuk memencet-mencet ponselnya, menelepon ke sana kemari
dengan suara yang sengaja dikeras-keraskan, “Ya, hallo, apa kabar? Bagaimana
bisnis kita? Halooo….”
Padahal ponsel itu tak ada pulsanya.
Ia juga punya kartu nama sekarang. Di kartu nama itu bertengger dengan
gagah namanya, tempat tinggal, dan jabatannya: Orang Miskin.
Ia memang jadi kelihatan keren sebagai orang miskin. Ia suka keliling
kampung, menenteng ponsel, sambil bersiul entah lagu apa. “Sekarang
anak-anakku tak perlu lagi repot-repot mengemis dengan tampang
dimelas-melaskan,” katanya. “Buat apa? Toh sekarang kami sudah nyaman jadi orang
miskin. Tak sembarang orang bisa punya Kartu Tanda Miskin seperti ini.”
Ia mengajakku merayakan peresmian kemiskinannya. Dibawanya aku ke warung
yang biasa dihutanginya. Semangkuk soto, ayam goreng, sambal terasi dan
nasi—yang tambah sampai tiga kali—disantapnya dengan lahap. Sementara aku
hanya memandanginya.
“Terima kasih telah mau merayakan kemiskinanku,” katanya. “Karena aku telah
benar-benar resmi jadi orang miskin, sudah sepantasnya kalau kamu yang membayar
semuanya.”
Sambil bersiul ia segera pergi.
Ketika tubuhnya digerogoti penyakit, dengan enteng orang miskin itu
melenggang ke rumah sakit. Ia menyerahkan Kartu Tanda Miskin pada suster jaga.
Karena banyak bangsal kosong, suster itu menyuruhnya menunggu di lorong.
“Beginilah enaknya jadi orang miskin,” batinnya, “dapat fasilitas gratis tidur
di lantai.” Dan orang miskin itu dibiarkan menunggu berhari-hari.
Setelah tanpa pernah diperiksa dokter, ia disuruh pulang. “Anda sudah
sumbuh,” kata perawat, lalu memberinya obat murahan.
Orang miskin itu pulang dengan riang. Kini tak akan pernah lagi takut pada
sakit. Saat anak-anaknya tak pernah sakit, ia jadi kecewa. “Apa gunanya kita
punya Kartu Tanda Miskin kalau kamu tak pernah sakit? Tak baik orang miskin
selalu sehat.”
Mendengar itu, mata istrinya berkaca-kaca.
Beruntung sekali orang miskin itu punya istri yang tabah, kata orang-orang.
Kalau tidak, perempuan itu pasti sudah lama bunuh diri. Atau memilih jadi
pelacur ketimbang terus hidup dengan orang miskin seperti itu.
Tak ada yang tahu, diam-diam perempuan itu sering menyelinap masuk ke
rumahku. Sekadar untuk uang lima ribu.
Suatu sore yang cerah, aku melihat orang miskin itu mengajak anak istrinya
pergi berbelanja ke mal. Benar-benar keluarga miskin yang sakinah, batinku. Ia
memborong apa saja sebanyak-banyaknya. Anak-anaknya terlihat begitu gembira.
“Akhirnya kita juga bisa seperti mereka,” bisik orang miskin itu pada
istrinya, sambil menunjuk orang-orang yang sedang antre membayar dengan kartu
kredit. Di kasir, orang miskin itu pun segera mengeluarkan Kartu Tanda Miskin
miliknya, “Ini kartu kredit saya.”
Tentu saja, petugas keamanan langsung mengusirnya.
Ia tenang anak-anaknya tak bisa sekolah. “Buat apa mereka sekolah? Entar
malah jadi kaya,” katanya. “Kalau mereka tetap miskin, malah banyak gunanya,
kan? Biar ada yang terus berdesak-desakan dan saling injak setiap kali ada
pembagian beras dan sumbangan. Biar ada yang terus bisa ditipu setiap menjelang
pemilu. Kau tahu, itulah sebabnya, kenapa di negeri ini orang miskin terus
dikembangbiakkan dan dibudidayakan.”
Aku diam mendengar omongan itu. Uang dalam amplop yang tadinya mau aku
berikan, pelan-pelan kuselipkan kembali ke dalam saku.
Takdir memang selalu punya cara yang tak terduga agar selalu tampak
mengejutkan. Tanpa firasat apa-apa, orang miskin itu mendadak mati.
Anak-anaknya hanya bengong memandangi mayatnya yang terbujur menyedihkan di
ranjang. Sementara istrinya terus menangis, bukan karena sedih, tapi karena
bingung mesti beli kain kafan, nisan, sampai harus bayar lunas kuburan.
Seharian perempuan itu pontang-panting cari utangan, tetapi tetap saja
uangnya tak cukup buat biaya pemakaman. “Bagaimana, mau dikubur tidak?” Para
pelayat yang sudah lama menunggu mulai menggerutu.
Karena merasa hanya bikin susah dan merepotkan, maka orang miskin itu pun
memutuskan untuk hidup kembali.
Sejak peristiwa itu, kuperhatikan, ia jadi sering murung. Mungkin karena
banyak orang yang kini selalu mengolok-oloknya.
“Dasar orang miskin keparat,” begitu sering orang-orang mencibir bila ia
lewat, “mau mati saja pakai nipu.”
“Apa dikira kita nggak tahu, itu kan akal bulus biar dapat sumbangan.”
“Dasarnya dia emang suka menipu, kok! Ingat nggak, dulu ia sering keliling
minta sumbangan, pura-pura buat bikin masjid. Padahal hasilnya ia tilep
sendiri.”
“Kalian tahu, kenapa dia tak jadi mati? Karena neraka pun tak sudi
menerima orang miskin kayak dia!”
Orang-orang pun tertawa ngakak.
Nasib buruk kadang memang kurang ajar. Suatu hari, orang miskin itu berubah
jadi anjing. Itulah hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Anak istrinya
yang kelaparan segera menyembelihnya. (*)